Oleh: Denny Kodrat
“Pemilu kali ini beda!” demikian bunyi spanduk besar milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu yang membedakan Pemilu kali ini dengan sebelumnya adalah untuk pertama kalinya pemilihan presiden secara langsung dilakukan. Harapannya, kepemimpinan nasional yang akan datang tidak hanya memiliki legitimasi secara konstitusi dan publik, tetapi juga akan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Namun, tidak sedikit rasa skeptis dimunculkan oleh pengamat politik dan sebagian publik, mengingat aktor-aktor yang memperebutkan kursi RI-1 masih didominasi oleh wajah-wajah lama dengan bermacam track record-nya. Demokrasi-sekular juga masih tetap menjadi gaya kepemimpinan yang digulirkan oleh hampir seluruh capres yang sedang bertarung. Satu pertanyaan retoris sederhana muncul di sini, dapatkah Indonesia menjadi sebuah negara besar yang sejahtera dalam arti sesungguhnya jika sistem dan gaya kepemimpinan nasionalnya hanya mengulang para pendahulunya?
Indikator Gagalnya Kepemimpinan
Panggung politik Indonesia terus diwarnai oleh praktik kekuasaan yang hipokrit, hidonistis, dan anarkis. Para penguasa membangun hegemoni kekuasaan politik dan ekonomi untuk memuaskan diri mereka dan kroni mereka sendiri dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Akibatnya, moralitas mereka sebagai pimpinan publik mersosot. Harga kekuasaan dapat ditukar dengan mata uang rupiah yang dibayar lewat rekening, amplop, atau langsung ke tangan para pemilik kekuasaan; atau dengan fasilitas jasa berharga. Sebaliknya, rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, tanpa kepestian masa depan. Tidak tampak tanda-tanda pembangunan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Semua itu adalah akibat praktik kekuasaan para penguasa yang tidak lagi mempertimbangkan aspek moral, apalagi agama yang menjadi inti kearifan peradaban.
Bercermin dari negara ideal produk Rasullullah saw., indikator sebuah kepemimpinan dikatakan gagal-tidak, sebenarnya dapat dilihat dengan pendekatan sederhana. Kepemimpinan dipandang gagal ketika negara tidak mampu memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya—seperti pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan hak dasar hidup manusia semisal sandang dan pangan; menegakkan supremasi hukum sehingga tidak terwujud apa yang disebut sebagai clean government dan good governance. Demikian pula sebaliknya.
Semasa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Indonesia mendapatkan suntikan dana sebesar 300.000 dolar AS dari UNDP (United Nations Development Program) untuk menciptakan good governance (Cides online). Namun, tentu saja, konsep sebuah good governance disesuaikan dengan keinginan UNDP. Dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan lembaga PBB untuk program pembangunan Januari 1997 ini, pemerintahan dikatakan baik apabila ia dapat mensinergikan pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam pengaturan negara. Bisa saja, sektor publik, seperti pendidikan, yang asalnya merupakan tanggung jawab pemerintah, dilimpahkan ke pihak swasta. Dari sinilah kemudian muncul istilah “swastanisasi pendidikan”. Dana besar UNDP tersebut ternyata tidak mampu menciptakan pemerintahan yang baik pada masa Wahid. Justru, wibawa Pemerintah ambruk didera kasus korupsi, salah satunya adalah kasus dana Bulog yang melibatkan Wahid sendiri.
Dapat dicermati bahwa korupsi menjadi masalah akut dalam kepemimpinan negeri ini. Parahnya lagi, kasus korupsi ini banyak menyeret para pejabat publik.
Masalah berikutnya adalah tarik-menarik dalam memperebutkan kekuasaan. Aliansi-aliansi politik yang dilakukan para elit untuk mencapai kursi kekuasaan tidak lagi menghiraukan platform dan ideologi. Elit dari parpol sekular dapat dengan mudah menggandeng pimpinan parpol Islam dengan tujuan mendapatkan dukungan dan memenangkan kursi RI-1, tanpa pernah menghiraukan pro-kontra konstituennya. Partai pemenang pada Pemilu Legislatif tetapi kalah dalam Pemilu Presiden terus merongrong eksekutif. Terjadilah kisruh di kabinet dan parlemen dan rakyatlah yang menjadi korban karena hak-haknya tidak terpenuhi.
Publik tidak hanya dilelahkan oleh kekisruhan di tingkat elit politik, namun juga ditekan oleh kebijakan pemerintah di sektor publik yang tidak “ramah kondisi” berupa, misalnya, terus melambungnya harga-harga pangan, BBM, pendidikan, telepon, pajak, dll. Hasilnya, kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah, dan tingkat kriminalitas meninggi. Bagi daerah-daerah tertentu yang kaya tetapi merasa dieksploitasi akhirnya memilih memisahkan diri. Situasi inilah yang akhirnya menciptakan kondisi “masyarakat sakit” sebagai akibat tidak beresnya manajemen kepemimpinan.
Kondisi seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan menimpa sebagian besar negeri-negeri Islam. Hampir semua negara tersebut memiliki karakteristik masalah yang sama, yaitu krisis kepemimpinan yang memicu masalah politik dalam negeri dan korupsi. Sebut saja Arab Saudi, yang sering dijadikan representasi sebagai “negara Islam” yang paling kaya dan makmur, yang tengah menghadapi krisis politik dan ekonomi. Sekitar 500 orang warga Saudi melakukan aksi unjuk rasa menuntut reformasi di bidang politik pada penghujung tahun 2003. Unjuk rasa ini semakin membuka adanya konflik vertikal antaranggota keluarga Kerajaan. Pangeran Abdullah yang menggantikan Raja Fahd—karena terserang stroke—tidak mendapatkan dukungan politik dari saudara-saudaranya yang lain. Akibatnya, pemerintahan Saudi secara politis mengalami stagnansi. Belum selesai mencairkan ketegangan politik di dalam negeri, datang masalah dari Newsweek yang mengaitkan keterlibatan anggota Kerajaan Saudi dengan jaringan al-Qaeda.
Kondisi perekonomian Saudi pun sedang berguncang. Kekuatan ekonomi Saudi yang dulu Gross Domestic Product-nya menyamai AS sebesar 20.000 poundsterling, sekarang jatuh ke kisaran 5000 poundsterling. Pengamat ekonomi memprediksi negara Saudi tidak akan memiliki pengaruh dan kekuatan di sektor ekonomi; Israel akan menggantikan posisi Saudi.
Penyebab Kegagalan Kepemimpinan
Jika ditelaah lebih mendalam, setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan gagalnya kepemimpinan khususnya di Indonesia. Pertama, person (individu) yang memegang kendali kepemimpinan tersebut. Sangat mungkin, stagnannya negara ini karena dipimpin oleh individu yang tidak qualified memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Sosok otoriter, anti kritik, hipokrit, arogan, tamak, tidak amanah, lemah (bersedia dikooptasi oleh negara asing), dan tentunya kedap terhadap kondisi rakyat yang dipimpinnya mungkin sudah pernah memimpin bangsa ini. Konsekuensinya keterpurukkan dan kecarutmarutan terjadi di sana sini. Memang, pada akhirnya wajar jika kebanyakan masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang salih secara individu, bersih dan memiliki karakter kuat dalam memimpin (strong leadership). Alasannya, tidak mungkin korupsi diberantas oleh seorang koruptor; hanya orang bersih dan kuatlah yang mampu memberantas tindak korupsi, terutama di kabinet dan departmennya. Akan tetapi, jika korupsi dan segala bentuk penyelewengan hanya dapat diberantas oleh seorang individu bersih an sich, tanpa melibatkan perubahan dan dukungan yang lain, semisal sistem-ideologi masyarakat, tampaknya pendapat ini perlu uji terlebih dulu. Namun demikian, sikap terpuji seorang pemimpin seperti rifq (lemah lembut dan santun), mubasyyir (penggembira), dan amanah secara langsung akan menumbuhkan sikap percaya masyarakat.
Kedua, sistem (sekular) yang diterapkan. Inilah yang sesungguhnya berkonstribusi secara penuh terhadap gagal-tidaknya sebuah kepemimpinan. Jika pemimpinnya orang bersih dan salih, namun ia menjalankan sistem yang rusak, tentu hasilnya pun akan rusak pula. Persis ibarat seorang arsitek bangunan yang sangat ahli dan pandai, namun ia harus menggunakan barang-barang kontruksi yang sudah sangat tua dan rapuh. Karena itu, orang yang qualified dan bersih tetapi menjalankan sistem sekular yang rusak adalah ibarat a good man in a wrong place. Sistem sekularlah yang banyak menghasilkan kebijakan yang merugikan publik. Jangankan untuk negeri-negeri Muslim, yang secara fitrah dan fikrah sudah jelas bertentangan, di negara asalnya saja, AS dan Barat, kebijakan sistem sekular ini hanya mengakomodasi kalangan borjuasi dan kapitalis. Kalangan kelas bawah tetap hidup dalam kesengsaraan. Singkatnya, kebijakan publik tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh karenanya, di AS muncul istilah, “The golden rule of democracy is those who have golds are ruler! (Aturan emas demokrasi adalah siapa saja yang punya emas (uang) dialah penguasa).”
Sistem sekular-lah yang sudah mengubah cara pandang seorang pemimpin nasional terhadap politik. Praktik kekuasaan untuk mengeruk uanglah yang ditonjolkan dalam berpolitik. Tidak aneh apabila banyak alokasi dana untuk publik bocor di tengah jalan karena dimanipulasi. Sistem sekularlah yang sudah lebih dari setengah abad mewarnai gaya kepemimpinan nasional Indonesia. Hasilnya, meski sudah lima presiden yang menahkodai Indonesia, adalah sama: korupsi, kolusi, kemiskinan, dan keterpurukkan di berbagai sektor tetap menjadi bagian integral dari wajah Indonesia.
Terakhir, ketergantungan terhadap negara asing. Indonesia mendapat dana pinjaman sebesar 3,4 miliar dari CGI untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, upaya ini lagi-lagi mengalami stagnansi; bukan saja terjadi kebocoran, namun juga semakin bertambahnya utang luar negeri Indonesia. Kemiskinan alih-alih dapat ditekan, malah semakin tinggi. Jika pendapatan penduduk Indonesia yang di bawah 2 dolar perhari menjadi standar kemiskinan, maka saat ini tingkat kemiskinan mencapai 53%. Untuk membayar berbagai macam cicilan luar negeri ini, Indonesia harus memangkas habis berbagai macam pos pendapatan, dan itupun masih kurang. Akhirnya, untuk menutupi kekurangan dana (defisit), pinjaman dari negara lain digunakan kembali untuk membiayai berbagai macam pengeluaran, termasuk pembayaran utang. Mudah ditebak, karena pemerintah sangat begitu tergantung pada pinjaman luar, otomatis intervensi negara donor akan sangat besar. Karena itu, tidak mengherankan apabila banyak kebijakan publik di berbagai bidang merupakan “pesanan” dari luar. Jika kondisi sudah seperti ini, wibawa seorang pemimpin yang seharusnya independen, mandiri, kuat, dan tidak menjadi alat negara asing akan hancur dengan sendirinya, baik di mata warganya, apalagi di mata sang Khalik.
Dalam konteks kekinian, untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil dan mampu mensejahterakan rakyatnya—dalam arti sesungguhnya—dibutuhkan perubahan terhadap tiga faktor di atas. Individu yang akan memimpin harus dipastikan kemuslimannya dan kapabilitasnya; benar-benar memiliki ketangguhan, kekonsistenan, dan kekuatan dalam memimpin. Sistem yang harus diterapkan adalah sistem yang nyata-nyata bersih (Islam), tunduk pada aturan ilahiah dan sesuai fitrah manusia; tentu saja dukungan dari komponen masyarakat berupa ketaatan dan muhâsabah (kontrol) yang menjadi pilar penjaga sistem harus ada. Terakhir, independent, dalam arti, tidak dapat diintervensi dan didominasi oleh negara asing.
Jika ketiganya tidak dapat terwujud, kepemimpinan kuat dan berwibawa yang mampu membawa negara ke arah yang baik masih akan menjadi sebatas wacana dan angan-angan semata. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []
Denny Kodrat adalah Pengamat Dunia Islam, tinggal di Bandung.

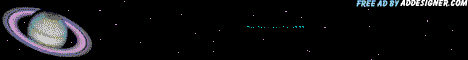
 13.20
13.20
 Remaja.com
Remaja.com


 Posted in:
Posted in: 

0 komentar:
Posting Komentar